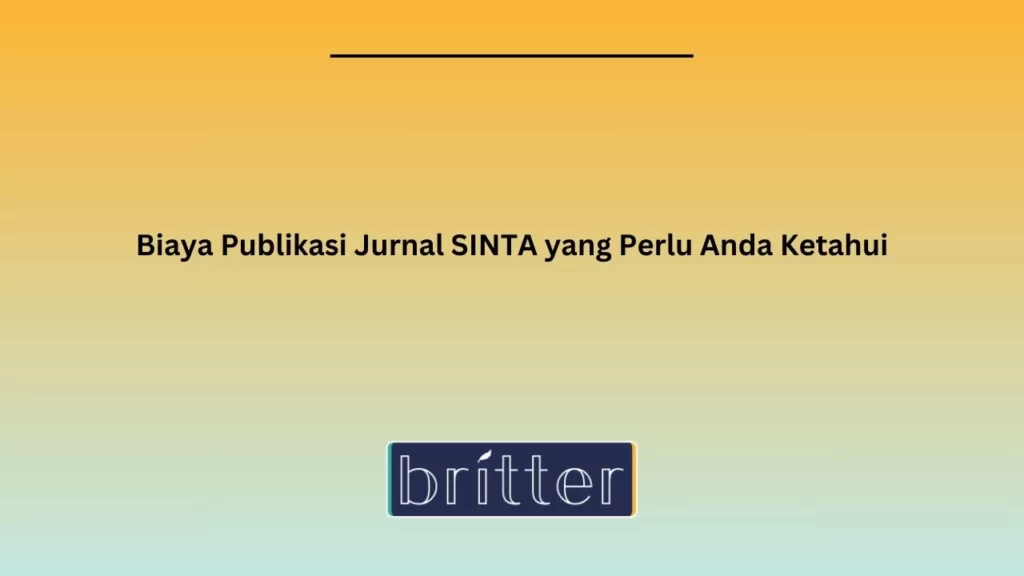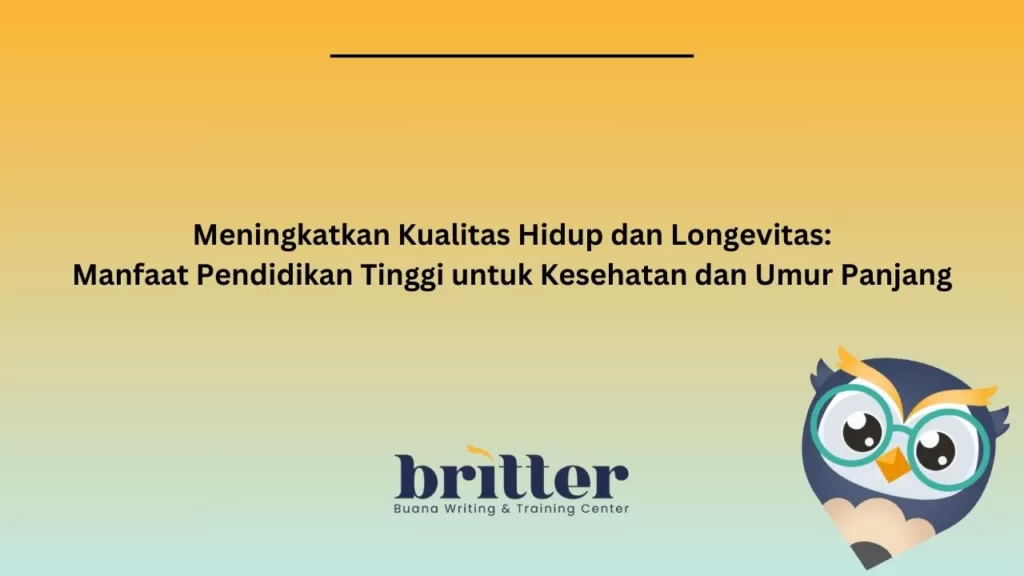Pendidikan tinggi sejatinya merupakan fondasi utama peradaban. Dari kampuslah lahir gagasan besar, pemikir kritis, dan elite intelektual yang membentuk arah masa depan bangsa. Namun, realitas hari ini menunjukkan sebuah kegentingan. Kampus, yang seharusnya menjadi medan hidup gagasan, perlahan kehilangan roh intelektualnya dan terjebak dalam rutinitas administratif yang kering makna.
Daftar Isi
- 1 Degradasi Keagungan Intelektual Kampus
- 2 Gagalnya Sistem Pendidikan Menengah Sebagai Fondasi
- 3 Teknologi dan Polusi Atensi
- 4 Ironi Subsidi Pendidikan Tinggi
- 5 Kampus sebagai Pabrik Laporan dan Data
- 6 Aktivisme Kosmetik Mahasiswa
- 7 Kampus dan Dosen dalam Zona Nyaman
- 8 Menggagas Kembali Kampus Berdampak
- 9 Visi Baru: Dari Reformasi Dokumen ke Revitalisasi Gagasan
- 10 Elite Intelektual dan Masa Depan Bangsa
Degradasi Keagungan Intelektual Kampus
Bukan sekadar provokasi, tetapi sebuah kenyataan pahit: kita telah menyaksikan kemerosotan kualitas intelektual di institusi pendidikan tinggi. Mahasiswa sebagai aktor utama kampus tidak lagi menjadikan perkuliahan sebagai ruang pematangan nalar, tetapi sebagai tahapan administratif yang mesti dilalui secepat mungkin. Gaya belajar berubah: bukan lagi eksploratif dan kritis, melainkan instan dan pragmatis.
Padahal, kampus harus menjadi tempat di mana keberanian berpikir, kedalaman analisis, dan keberpihakan pada realitas sosial diasah dan dibentuk. Kini, mahasiswa hadir sekadar mengejar absen, menyusun tugas tanpa makna, dan lulus secepat mungkin demi gelar dan pekerjaan, bukan ilmu dan pemahaman.
Gagalnya Sistem Pendidikan Menengah Sebagai Fondasi
Kondisi ini tidak muncul begitu saja. Sistem pendidikan menengah atas yang gagal membekali siswa dengan kemampuan berpikir kritis dan literasi dasar menjadi salah satu akar masalah. Akibatnya, mahasiswa baru tidak terbiasa membaca buku secara utuh, menulis reflektif, atau berdiskusi substansial. Mereka mengalami culture shock saat harus berhadapan dengan bacaan ilmiah atau tugas analisis mendalam.
Tentu saja tidak semua mahasiswa demikian. Namun, tren penurunan kemampuan literasi akademik ini tidak bisa diabaikan. Banyak dosen yang mengeluhkan penurunan drastis dalam kualitas penulisan, daya kritis, hingga kemampuan logis mahasiswa dalam satu dekade terakhir.
Teknologi dan Polusi Atensi
Kehadiran teknologi dan media sosial semakin memperparah kondisi ini. Alih-alih memanfaatkan internet untuk riset dan pengembangan diri, mahasiswa justru lebih banyak menghabiskan waktu di TikTok, Instagram, atau YouTube tanpa arah. Fokus mereka terpecah. Polusi atensi menjadikan kemampuan berpikir mendalam dan fokus jangka panjang nyaris musnah.
Tentu teknologi bukan musuh. Ia adalah alat. Namun ketika alat tersebut tidak digunakan secara bijak, maka fungsinya sebagai penunjang ilmu berubah menjadi pengalih perhatian. Dalam konteks ini, literasi digital menjadi kebutuhan mendesak yang belum dijawab serius oleh kampus.
Baca Juga: Membongkar Mitos Indeksasi: Menilai Kualitas Penelitian Bukan Sekadar Scopus dan WoS
Ironi Subsidi Pendidikan Tinggi
Di perguruan tinggi negeri, ironi lain muncul. Pemerintah menggelontorkan anggaran besar untuk membiayai pendidikan tinggi. Namun, mahasiswa yang menjadi penerima manfaatnya, tidak memiliki kesadaran akan tanggung jawab moral atas subsidi tersebut. Mereka merasa itu adalah hak mutlak, bukan amanah yang mengandung konsekuensi etik.
Situasi ini menjadi kontradiksi. Negara bersungguh-sungguh membiayai, namun proses akademik dijalani secara sembrono. Jika dibiarkan, ini bukan hanya akan memboroskan anggaran, tetapi juga mengakibatkan kerugian jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia bangsa.
Kampus sebagai Pabrik Laporan dan Data
Lebih menyedihkan lagi adalah bagaimana kampus saat ini lebih sibuk mengurus akreditasi, laporan evaluasi diri, dan angka-angka capaian kinerja, daripada mendidik manusia. Kata “output”, “outcome”, dan “impact” berseliweran dalam dokumen administrasi, namun jarang dimaknai secara substantif.
Dosen ditekan untuk publikasi bukan demi berbagi ilmu, tapi demi akreditasi. Mahasiswa ditekan untuk cepat lulus demi statistik. Kampus menjadi pabrik angka, bukan inkubator pemikiran. Di ruang-ruang rapat, keberhasilan diukur dari laporan, bukan dari pengaruh nyata di masyarakat.
Aktivisme Kosmetik Mahasiswa
Kita acap kali berbangga melihat mahasiswa aktif dalam organisasi. Tetapi bila aktivitas mereka hanya berkutat pada proposal, kaos, dan banner, maka itu hanyalah aktivisme kosmetik. Ia tidak mengangkat kualitas intelektual, tidak memperkuat daya kritis, dan tidak memberi kontribusi pada perubahan sosial.
Organisasi mahasiswa semestinya menjadi ruang tempaan karakter dan gagasan. Namun kini, tak jarang organisasi hanya menjadi ajang perebutan posisi, bukan ruang perjuangan intelektual atau sosial.
Kampus dan Dosen dalam Zona Nyaman
Krisis ini juga diperparah oleh dosen dan birokrasi kampus yang nyaman dengan status quo. Dosen tidak lagi menjadi inspirator, melainkan pengisi borang. Birokrat kampus sibuk mengejar kenaikan tunjangan kinerja, bukan mendorong perubahan kurikulum atau menciptakan ruang inovasi.
Padahal, seharusnya kampus menjadi ruang yang selalu gelisah, tidak puas, dan terus mencari cara untuk menjawab tantangan zaman. Jika semuanya hanya menjalani rutinitas tanpa semangat perubahan, maka yang tersisa hanyalah kelumpuhan struktural.
Menggagas Kembali Kampus Berdampak
Lalu, apa yang harus kita lakukan?
Kita perlu menggugat ulang makna “kampus berdampak”. Bukan sekadar jargon atau kalimat manis dalam visi-misi, tetapi sebagai prinsip kerja yang memandu seluruh kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Kampus berdampak adalah kampus yang:
- Membentuk pemikir kritis, bukan hanya pencari kerja.
- Menjadi pusat solusi atas persoalan bangsa.
- Menjadi tempat diskusi lintas disiplin dan keberpihakan pada publik.
- Mendorong dosen menjadi mentor kehidupan, bukan hanya pengajar silabus.
- Membangun kemitraan aktif dengan komunitas lokal dan dunia industri secara substantif.
Visi Baru: Dari Reformasi Dokumen ke Revitalisasi Gagasan
Sudah saatnya kita bergerak dari reformasi dokumen ke revitalisasi gagasan. Kampus harus menjadi tempat gagasan liar diuji, tempat diskusi keras digembleng, dan tempat nilai-nilai luhur ditegakkan. Ini hanya mungkin jika kita memulai dari dalam diri setiap civitas akademika.
Dosen perlu menyalakan kembali “api akademik”-nya. Mahasiswa harus ditantang untuk berpikir lebih keras dan menulis lebih dalam. Pengelola kampus harus lebih peduli pada kualitas lulusan daripada jumlah publikasi.
Elite Intelektual dan Masa Depan Bangsa
Akhirnya, pertaruhan pendidikan tinggi adalah pertaruhan masa depan bangsa. Jika kita gagal membentuk elite intelektual yang kuat, maka bangsa ini akan rapuh. Tanpa elite intelektual, kita akan mudah terombang-ambing oleh populisme semu, hoaks, dan kebijakan reaktif.
Kampus harus mengambil kembali peran strategisnya sebagai penjaga akal sehat bangsa. Jika tidak, maka kejatuhan pendidikan tinggi hanyalah soal waktu.